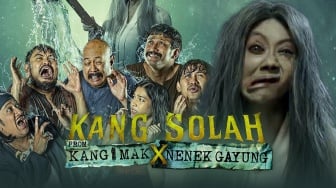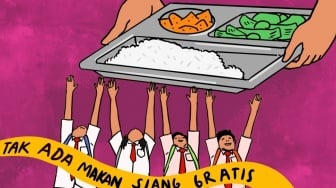Suara.com - Indonesia menjadi negara penghasil sampah makanan rumah tangga terbesar di Asia Tenggara. Menurut laporan UNEP 2024, totalnya mencapai 14,73 juta ton per tahun.
Tak berhenti di situ, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat timbunan sampah nasional dari 290 kabupaten/kota mencapai 31,9 juta ton hingga Juli 2024. Ironisnya, sekitar 7,2 juta ton atau 34,29 persen dari jumlah itu belum terkelola dengan baik.
Masalah ini bukan sekadar soal data. Sampah yang berserakan di pojok jalan, menumpuk di TPS, mencemari air dan udara, serta membentuk tumpukan bau di tengah lingkungan padat penduduk adalah realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari.

Namun solusi yang diupayakan selama ini masih terfragmentasi. Pemerintah telah membuat kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, perusahaan mulai menerapkan prinsip produksi bersih, dan masyarakat bergerak melalui komunitas dan aktivisme akar rumput. Sayangnya, upaya-upaya ini belum berjalan secara terintegrasi.
Berangkat dari keresahan tersebut, Core Indonesia menyelenggarakan forum diskusi terbuka bertajuk “Membangun Ekosistem Pengelolaan Sampah yang Holistik” di Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025).
Acara ini mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, hingga orang muda.
Roleplay untuk Mengerti Kompleksitas
Yang menarik, sesi utama forum bukan hanya berbentuk diskusi, melainkan simulasi atau roleplay yang dirancang agar peserta merasakan langsung peran berbagai pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah. Mereka dibagi ke dalam kelompok stakeholder, aktivis, masyarakat umum, pelaku industri, dan akademisi.
Hasil diskusi tiap kelompok menunjukkan betapa pentingnya empati lintas sektor dan perlunya sinergi. Dari kelompok aktivis misalnya, muncul gagasan kampanye digital yang lebih dekat dengan generasi muda, seperti menggunakan TikTok atau Instagram dengan pendekatan emosional dan partisipatif.
Baca Juga: Elektronik yang Larut dan Ramah Lingkungan: Masa Depan Tanpa Sampah Teknologi?
“Kampanye digital masih sangat efektif untuk menjangkau Gen Z dan milenial. Tapi untuk menjangkau masyarakat yang tidak terhubung teknologi, komunitas lokal seperti RT dan karang taruna tetap penting,” ungkap salah satu peserta dari kelompok aktivis.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya pendanaan alternatif, seperti pemanfaatan dana desa untuk memberi insentif kepada masyarakat yang aktif mengelola sampah.
Skema “sampah jadi cuan” seperti bank sampah yang ditukar dengan subsidi kesehatan atau diskon warung juga dianggap sebagai langkah strategis.
Mendorong Regulasi yang Inklusif
Dari kelompok regulator dan akademisi, diskusi menyoroti perlunya sense of urgency dari pemerintah dalam menghadapi krisis sampah. Pendekatan kebijakan dinilai masih terlalu fokus pada sanksi, belum cukup pada penguatan kebiasaan.
“Alih-alih hanya memberlakukan denda, regulasi seharusnya mendorong kebiasaan positif lewat pendekatan yang inklusif,” kata peserta lain.
Mereka juga mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berbasis data.
"Pemerintah perlu naskah-naskah rekomendasi yang tematis dan bisa mengkuantifikasi dampak lingkungan dan ekonomi dari sampah,” tegas salah satu peserta.
Selain itu, diskusi menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih tegas, penyediaan alat pengolah sampah yang terjangkau, serta model pengelolaan yang memberi benefit langsung ke masyarakat.
Contohnya, Reverse Vending Machine (RVM) di desa yang menukar botol plastik dengan kupon diskon atau voucher game.
Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Kesimpulan dari sesi ini menegaskan satu hal, bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk masalah sampah. Semua pihak perlu berjalan beriringan, bukan bekerja sendiri-sendiri.
Core Indonesia berharap metode interaktif seperti roleplay dapat memperkuat kesadaran bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis, tapi juga soal membangun kultur kolaboratif dan saling percaya antar pemangku kepentingan.