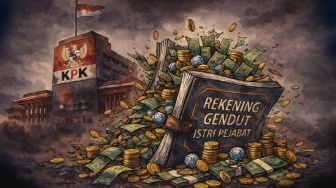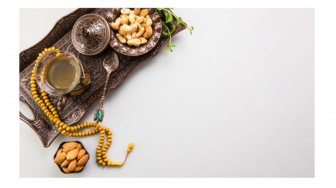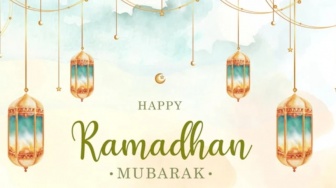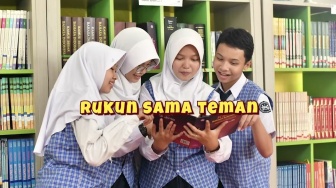Suara.com - Perubahan iklim bukan lagi sekadar omon-omon belaka. Pulau Sabu dan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan kenyataan pahit itu. Sebut saja, pola hujan tak menentu, kekeringan berkepanjangan, dan ancaman bencana, kerap menimpa warga. Mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian dan laut berada di bawah tekanan hebat.
Laksmi Dhewanthi, Inspektur Utama BPLH 2025 dan Focal Point Panitia Pengarah Nasional GEF SGP Indonesia, memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Ya, Indonesia dan sluruh dunia kini mengalami tahun yang paling panas. Betapa tidak, saat itu, diperkirakan kenaikan suhu di semua lapisan bumi sudah melampaui 1,1 derajat Celcius.
“Indonesia dan seluruh dunia ini mengalami tahun yang paling panas. Kita tidak punya waktu lagi untuk menambah satu derajat pun," terang Laksmi Dhewanthi, dalam forum diskusi tematik di Aula Rapat Gedung Pemerintah Kabupapaten Sabu Raijua, Kamis (24/7/2025).
Pernyataan tersebut tak pelak menggarisbawahi urgensi krisis iklim yang kini menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Sabu dan Raijua. Bukan hanya suhu yang meningkat, melainkan juga bencana yang mengintai dari berbagai sisi.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 3.472 kejadian bencana di Indonesia. Nah, sebanyak 80 persen di antaranya dipicu faktor perubahan iklim. Untuk wilayah kepulauan terpencil, dampaknya terasa jauh lebih nyata dan menakutkan.
Pulau Sabu dan Raijua, contohnya. Kenaikan permukaan air laut, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem yang dapat mengisolasi wilayah menjadi ancaman. Ekosistem pesisir seperti padang lamun, mangrove, hingga terumbu karang turut merasakan tekanan. Di saat bersamaan, akses terhadap sumber air bersih juga makin sulit akibat kekeringan dan degradasi lingkungan.

Sebagai wilayah agraris dan pesisir, ancaman ini mengganggu tatanan ekonomi lokal. Pertanian yang sangat bergantung pada musim dan air menjadi tidak stabil. Perikanan pun terganggu oleh cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem laut.
Untuk itu, Laksmi menekankan pentingnya adaptasi yang nyata di tingkat lokal. “Kita tidak punya waktu untuk menambah emisi gas rumah kaca karena bumi sudah tidak bisa lagi menoleransi,” ujarnya lagi.
Berbagai strategi adaptasi pun ditawarkan: mulai dari adaptasi permukiman pesisir, diversifikasi pertanian dengan komoditas tahan iklim, pembangunan embung untuk air bersih, pelestarian ekosistem pesisir, hingga pengembangan kampung iklim berbasis komunitas.
Sayangnya, masalah struktural seperti tata ruang hutan justru menambah beban. Banyak kawasan produktif justru masuk ke dalam kawasan hutan lindung, sehingga menyulitkan pengembangan pertanian dan pembangunan desa.
“Kalau hutan lindungnya fungsinya kan boleh untuk konservasi area dan air. Tetapi hutan ini juga boleh dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu-nya,” ujar Bambang Supriyanto, eks Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK.
Menurutnya, dari 80.000 hektare alokasi perhutanan sosial di Nusa Tenggara Timur, baru sekitar 30.000 hektar yang terealisasi. Artinya, ada potensi besar yang belum tersentuh dan bisa dimanfaatkan, termasuk di Sabu Raijua.
Kondisi itu juga diperkuat oleh keluhan dari pemerintah daerah. Seorang peserta dari Dinas Pertanian menyampaikan keresahan yang selama ini dirasakan di lapangan.
“Kami dinas pertanian ini yang betul-betul merasakan efek dari kawasan hutan ini. Satu desa di Rekore itu 100 persen, itu semua hutan berlindung. Malangnya pertanian desa Rekore itu adalah penghasil bawang terbesar di Sabu Raijua,” katanya.
Selain tekanan terhadap lahan dan iklim, warga juga menghadapi tantangan energi dan pembangunan. Penggunaan kayu bakar untuk produksi gula lontar masih masif, dan penambangan pasir memicu abrasi. Hal ini memperburuk kerentanan lingkungan.