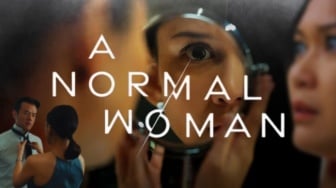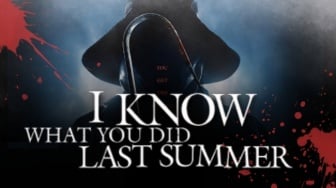Suara.com - Di tengah tekanan krisis iklim dan keterbatasan infrastruktur ekonomi, gula lontar atau gula sabu menjadi ‘harta karun’ terpendam di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Sayang, komoditas unggulan ini belum digarap maksimal. Padahal, ada peluang besar gula lontar untuk bisa menembus pasar ekonomi global.
Viringga Kusuma dari Amati Indonesia merasa optimistis atas masa depan gula lontar khas sabu. Apalagi, jika dipadukan dengan strategi pemasaran modern, diyakini gula lontar bisa menembus pasar global. Ditambah lagi, ada narasi baik di balik gula dari tanaman lontar ini yang dihasilkan oleh mayoritas masyarakat Sabu yang merupakan petani gula.
"Gula sabu punya potensi besar karena memiliki narasi baik oleh mayoritas masyarakat sabu yang merupakan pengolah dan penghasil gula aren,” kata Viringga dalam diskusi yang digagas GEF SGP Indonesia bertajuk “Membangun Ketahanan Iklim dan Ekonomi Lokal Pulau Sabu & Raijua melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” yang dihelat di Gedung Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Kamis (24/7/2025).
Karena itu pula, menurut Viringga, perlu adanya sebuah promosi clean label di ambang tingginya potensi dari pohon lontar tersebut. Konsep clean label ini diharapkan bisa membuat olahan gula sabu dalam dilirik dan dihargai. Terlebih, gula sabu ini menjadi salah satu komoditas yang dipamerkan di Indonesian House of Amsterdam, Belanda.
Pasar gula alami di India, Vietnam, dan Belanda menunjukkan permintaan tinggi akan produk gula yang sehat dan transparan. Karena itulah, penerapan clean label ini dibutuhan untuk memastikan kualitas bahan baku dari pohon lontar yang sehat, proses produksi yang higienis, dan penggunaan wadah yang bersih tanpa bahan tambahan kimia.
Langkah ini bukan semata soal branding, tapi juga soal market trust. Gula lontar Sabu yang selama ini diproduksi tradisional sebenarnya memiliki cerita kuat, nilai budaya, hingga manfaat kesehatan. Dengan penyesuaian standar mutu, sertifikasi organik dan halal, serta pengemasan yang menarik, produk ini bisa menjadi primadona baru Indonesia.
Dalam makalah di jurnal International Review of Humanities Studies, Daniel Hariman Jacob, dosen Universitas Indonesia, menuliskan pohon lontar dan masyarakat Sabu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Bahkan, warga setempat bersyukur dengan adanya pohon lontar yang memberikan sumber makanan pokok mereka: gula sabu.
Daniel menyebutkan mata pencarian utama masyarakat Sabu adalah bertani ladang dan menyadap lontar. Mereka mengolahnya menjadi gula. Meski sesekali bertanam kacang hijau maupun padi, masyarakat Pulau Sabu menyadap lontar dan memasak gula merupakan kegiatan penduduk Sabu sepanjang tahun.

Untuk mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata, usaha mikro kecil (UMK) lokal juga membutuhkan strategi menyeluruh dan dukungan lintas sektor. Hal ini diafirmasi Radityo Putro Handrito, Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang turut hadir dalam forum diskusi tersebut.
“Seharusnya proses bisnis berkelanjutan tidak berarti antara proses bisnis berkelanjutan dalam bidang ekonomi. Maksudnya, ekonomi dan lingkungannya harusnya berjalan secara beriringan. Ekonomi tumbuh, tapi kemudian lingkungannya tidak kelihatan. Lingkungannya kelihatan, tapi kemudian ekonominya juga tidak kelihatan sehingga harus beriringan,” katanya.
Radityo menyoroti pentingnya produksi berkelanjutan. Artinya, UMK harus menjaga kelestarian pohon lontar, sebagai sumber utama bahan baku gula sekaligus mengoptimalkan proses pengolahan, mulai dari panen nira hingga distribusi produk jadi. Kapasitas pengusaha juga harus diperkuat lewat pelatihan, pendampingan usaha, serta akses ke teknologi.
Nah, salah satu teknologi yang digagas dalam forum ini adalah alat pemasak gula lontar bertenaga surya, yang dikembangkan oleh Yayasan Cemara. Selain lebih ramah lingkungan, alat ini juga mampu meningkatkan efisiensi dan higienitas produksi.
"Alat ini adalah alat masak gula. Alat masak gula Sabu yang kita combine dengan teknik kita yang bersumber matahari," ujar salah satu pengembang dari Yayasan Cemara.
Menurutnya, alat ini mampu menghasilkan gula berkualitas tinggi, lebih higienis dibanding metode tradisional yang masih mengandalkan kayu bakar. Ini membuka peluang peningkatan daya saing di pasar sekaligus menekan deforestasi.
Tak kalah penting adalah strategi pemasaran. Banyak produk UMK lokal gagal bukan gara-gara kualitas rendah, melainkan tidak memiliki narasi dan platform promosi memadai. Karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan media sosial menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar.
Radityo pun mendorong penguatan kelembagaan UMK agar lebih siap bersaing. Koperasi produksi, kemitraan dengan swasta, hingga kolaborasi dengan akademisi dan pemerintah bisa menjadi pendorong percepatan.
Selain itu, diversifikasi produk dan pemasaran terintegrasi melalui branding yang kuat akan meningkatkan nilai jual produk lokal Sabu Raijua. Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi juga sangat penting. Kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta adalah kunci menghadapi tantangan dan mengoptimalkan potensi Sabu Raijua.
Sekadar informasi, perubahan iklim menjadi fenomena getir yang dirasakan masyarakat Pulau Sabu dan Pulau Raijua–yang termasuk wilayah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Meski kekayaan alamnya melimpah, krisis iklim menggentayangi kehidupan warga, seperti pola hujan tak menentu, dan kekeringan berkepanjangan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Sabu Raijua, Thobias Uly, dalam diskusi tematik yang digagas GEF SGP Indonesia dan Yayasan Pikul dengan tema Membangun Ketahanan Iklim dan Ekonomi Lokal Pulau Sabu & Raijua melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Gedung Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Kamis (24/7).
Thobias menyoroti kemandirian, kolaborasi, dan adaptasi sebagai pilar utama Sabu Raijua menghadapi tantangan iklim dan ekonomi. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menawarkan solusi dan komitmen bersama.
Diskusi ini secara jelas menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkan Sabu Raijua sebagai pulau yang tangguh terhadap iklim, mandiri secara ekonomi, dan lestari dalam sumber daya alamnya.