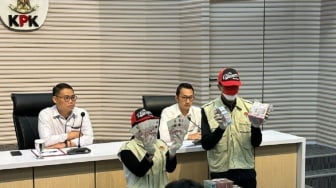Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tak hanya dihadapkan pada kompleksnya kemelut sosial-politik, tetapi juga intoleransi dan radikalisme terhadap perempuan yang semakin menajam.
Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Mereka tumbuh subur di tengah minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar warga, meningkatnya konservatisme keagamaan, serta lemahnya edukasi publik soal kesetaraan gender. Dalam konteks ini, perempuan kerap kali menjadi sasaran utama.
Intoleransi Gender Memburu Perempuan dari Ruang Doa hingga Sekolah
Pada Mei 2024, publik dikejutkan oleh serangan terhadap 12-15 orang mahasiswa Universitas Pamulang yang sedang melangsungkan doa Rosario di Cisauk, Tangerang Selatan. Mereka diserang oleh sejumlah warga yang mengaku merasa terganggu dengan ibadah tersebut. Atas insiden ini, ada dua korban perempuan yang alami luka sayatan senjata tajam.
Merespons kasus tersebut, Komnas Perempuan mengecam keras tindakan intoleransi serta radikalisme itu melalui siaran pers. Tindakan kekerasan ini tidak hanya mempertontonkan rendahnya toleransi terhadap kebebasan beragama dan perbedaan budaya, etnis, maupun ras, tetapi turut menunjukkan bagaimana perempuan menjadi kelompok paling rentan atas tindakan intimidasi hingga kekerasan berbasis gender.
Pada kasus lainnya, Juli 2022, jagat maya sempat digemparkan oleh laporan kasus pemaksaan pemakaian hijab di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan Bantul, Yogyakarta, yang membuat siswi tersebut depresi. Mirisnya, pelaku dari tindakan ini justru dilakukan oleh guru bimbingan konseling, wali kelas, dan guru agama. Tak hanya itu, bahkan pada beberapa kasus lainnya, pemaksaan pemakaian hijab dialami oleh siswi dengan identitas agama ataupun keyakinan berbeda di berbagai sekolah negeri di Indonesia.
Tak berhenti dalam memaksa dan mengatur cara berpakaian, berbagai sekolah negeri juga masih marak mewajarkan praktik razia menstruasi oleh guru terhadap para siswinya, dengan dalih menguji kejujuran murid. Salah satu kasus terlapor terjadi di salah satu SMA Negeri di Bogor pada September 2022 lalu. Para siswi yang mengaku menstruasi dan tak bisa ikut salat, dikumpulkan oleh guru mereka, lalu bagian rok belakang diraba untuk membuktikan kebenarannya.
Komnas Perempuan menyebut bahwa peristiwa serupa terus berulang dan banyak dialami oleh siswi maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai daerah. Pemaksaan yang menenteng alasan agama tersebut rentan mengakibatkan traumatis berkepanjangan, ketakutan, hilangnya rasa aman, dan perlindungan untuk berbuat sesuatu.
Bukan hal mustahil apabila masih banyak korban yang merasa takut dan tidak aman untuk melaporkan tindak pemaksaan dan larangan itu, sehingga terjadi pembiaran begitu saja. Berulangnya peristiwa serupa menunjukkan masih kuatnya politik identitas yang berkaitan dengan praktik diskriminasi.
Sementara itu, CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) mencapai 330.097 kasus, meningkat 14,17% dari tahun sebelumnya. Kekerasan ini meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, hingga kekerasan berbasis agama dan keyakinan.
Baca Juga: Ruang Aman untuk Penyintas: Komunitas Broken but Unbroken Hadirkan Dialog dan Pemulihan
Data ini diperkuat oleh laporan Setara Institute yang menyebutkan adanya 329 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2023, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan kelompok minoritas. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam lima besar wilayah dengan tingkat intoleransi tertinggi.
Patriarki Bersemayam dalam Dalil Neraka–Surga Kelompok Radikal
Konstruksi gender dalam masyarakat patriarkal turut berperan besar dalam kejahatan sistemik dan struktural ini. Lewat intoleransi serta radikalisme berbasis dalil-dalil neraka-surga yang amat misoginis, para pelaku merasa perlu menegakkan dominasi mayoritas, mempertahankan kontrol atas tubuh hingga menghukum hidup perempuan yang dianggap menyalahi norma agama maupun sosial.
Akibatnya, nyaris tubuh hingga kehidupan utuh perempuan menjadi objek pengawasan yang ketat. Perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan norma mayoritas sering kali menjadi target kekerasan verbal maupun fisik. Kelompok-kelompok radikal yang mengejar agenda konservatif acap kali menjadi dalih untuk memperkenalkan kebijakan yang membatasi hak-hak dasar perempuan sebagai manusia.
Pola kekerasan sistemik ini nyaris selalu sama, ditandai tindakan main hakim sendiri dengan upaya pemaksaan, pelarangan dan atau perundungan hingga tak jarang membuat para korban meregang nyawa.
Perempuan tidak hanya menjadi korban dalam ekstremisme kekerasan, tetapi juga dijadikan alat oleh kelompok radikal untuk memperluas pengaruh. Mereka direkrut melalui manipulasi ideologi, dijadikan istri para "pejuang syahid", atau dipaksa tunduk pada sistem yang merampas hak asasi mereka.
Ironisnya, dalam beberapa kebijakan pemerintah, kita juga menemukan jejak-jejak konservatisme negara. Misalnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU Pornografi yang selama ini kerap digunakan untuk menjerat perempuan, baik sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa dan terpidana.
Komnas Perempuan melaporkan bahwa sejak UU ini disahkan hingga tahun 2021, tidak satupun yang menghukum pelaku industri pornografi atau pemilik situs porno di dunia maya. Milyaran situs porno masih tersedia dan begitu mudah diakses oleh siapa saja hingga saat ini, tak terkecuali usia anak. Bukannya melindungi, regulasi semacam ini justru memperparah stigma terhadap perempuan dan mengukuhkan kontrol terhadap tubuh mereka.
Jejak konservatisme negara lainnya yang tak boleh luput dari ingatan, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 yang mengatur penggunaan busana di lingkungan pendidikan negeri dan kantor pemerintahan. Putusan ini barang pasti menghambat pencegahan dan penanganan kebijakan-kebijakan di daerah yang memuat diskriminasi, khususnya terkait pemaksaan busana di lingkungan pendidikan.
Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya—tercatat sebesar 0,421, menjadi penurunan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Namun, angka ini tidak menggambarkan kenyataan di lapangan. Penurunan angka IKG belum sebanding dengan upaya struktural untuk mencerabut borok patriarki dan kekerasan berbasis gender yang sudah mengakar.
Intoleransi dan radikalisme terhadap perempuan bukan sekadar persoalan moral dan agama, tetapi pelanggaran hak asasi manusia, bahkan yang paling dasar sekalipun. Negara gagal memenuhi mandat konstitusionalnya untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi hingga ekstremisme. Kita butuh kebijakan yang berpihak, masyarakat yang sadar, dan media yang adil. Terutama, ruang aman bagi perempuan untuk hidup, sekolah, bekerja, dan mengekspresikan diri tanpa takut diintimidasi dan terbunuh.
Darurat Keberpihakan, Negara Harus Berhenti Membuat Jejak Konservatisme Terhadap Perempuan
Negara, dalam hal ini pemerintah, harus menunjukkan keberpihakan penuh pada hak asasi perempuan, bukan justru tunduk pada tekanan kelompok konservatif yang kerap menjual narasi moralitas untuk membatasi ruang gerak perempuan, terutama di institusi pendidikan yang justru mengancam keamanan para muridnya.
Dalam situasi genting ini, saya mengumpulkan berbagai rekomendasi Komnas Perempuan dari tahun 2022 hingga 2024 terkait intoleransi kebebasan beragama dan keyakinan serta pemaksaan pakaian di institusi pendidikan maupun lembaga pemerintahan, yang nyatanya masih begitu relevan hingga hari ini.
Adapun rekomendasi tersebut, yakni;
Pertama, pemerintah harus segera menghentikan penanganan kasus intoleransi secara sembunyi-sembunyi dan perdamaian semu antara pelaku terhadap korban. Hal tersebut hanya akan menyelesaikan persoalan di permukaan dan menyisakan luka mendalam pada korban, bahkan berpotensi menempatkan korban sebagai korban berkali-kali.
Kedua, pemerintah perlu membentuk kelompok kerja khusus. Fungsinya untuk penanganan kebijakan diskriminatif untuk menyusun perencanaan sistemik dalam mengupayakan percepatan penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif di berbagai daerah.
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan Putusan MA No.17P/HUM/2021. Menurut Komnas Perempuan, Kantor Staff Presiden, Kemenkopolhukam, dan Kemenko PMK harus melakukan koordinasi dengan melibatkan berbagai lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI untuk menyikapi secara sistemik Putusan MA No.17P/HUM/2021 tersebut.
Sangat penting juga untuk melibatkan kelompok perempuan dalam membangun rekonsiliasi berkeberlanjutan, sehingga terbangun nilai toleransi atas keberagaman, serta membangun rasa damai antar kelompok yang beragam.
Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan sosialisasi dan mengawasi larangan diskriminasi dan tindakan kekerasan atas dasar apa pun. Strategi pencegahan dan penanganan bisa melalui perluasan layanan dan informasi pengaduan di lingkungan pendidikan, yang dapat diakses siswa maupun wali murid yang mengalami diskriminasi serta kekerasan di lingkungan pendidikan.
Keempat, pemerintah daerah dan DPRD perlu meninjau ulang secara menyeluruh kebijakan di daerah. Termasuk kebijakan yang dikeluarkan sekolah negeri untuk memastikan langkah koreksi pada praktik diskriminatif. Mengupayakan advokasi bagi pemenuhan HAM, penghormatan pada kebhinekaan, serta memastikan perempuan korban intoleransi dan keluarganya mendapatkan rehabilitasi sosial berkelanjutan.
Kelima, masyarakat harus memanfaatkan mekanisme keluhan yang telah disediakan oleh kementerian/lembaga terkait. Salah satunya yakni hotline yang dikembangkan oleh Kemendikbud untuk keluhan mengenai kebijakan dan praktik diskriminatif di sekolah. Tujuannya untuk mendorong perubahan dan layanan pengaduan yang disediakan lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI.
Tak hanya itu, Komnas Perempuan perlu mendapatkan dukungan lebih besar—baik dari sisi anggaran maupun wewenang hukum—agar mampu menjalankan mandat perlindungan HAM perempuan secara maksimal. Mereka juga perlu memperkuat sistem rujukan dan layanan untuk korban kekerasan berbasis gender.
Sementara, media memiliki tanggung jawab besar untuk tidak andil menyebarkan narasi yang menyudutkan korban. Penggunaan istilah-istilah seperti "wanita penggoda" atau "pakaian tidak pantas" dalam pemberitaan hanya akan melanggengkan budaya menyalahkan korban (victim blaming).
Kemudian, komunitas penyintas dan organisasi masyarakat sipil harus terus diperkuat. Mereka adalah garda terdepan dalam advokasi, edukasi, dan pemulihan korban. Dalam hal ini, dukungan terhadap inisiatif dari berbagai komunitas akar rumput menjadi sangat penting.