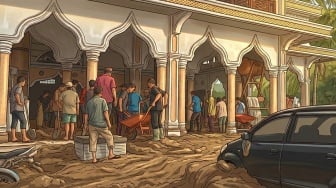Suara.com - Kisah Bripka Fardiansyah, polisi di Bangka Belitung yang bekerja sebagai badut usai jam dinas, viral dan menuai decak kagum.
Publik memujinya sebagai simbol kejujuran, kerja keras, dan dedikasi pada keluarga.
Namun, di balik gelombang apresiasi yang mengharukan, tersimpan sebuah pertanyaan fundamental yang lebih dalam dan sering kali canggung untuk dibicarakan.
Mengapa seorang polisi yang telah mengabdi selama 17 tahun masih harus mencari pekerjaan sampingan yang menuntut fisik dan mental?
Kisah inspiratif Bripka Fardiansyah, jika dilihat dari kacamata ekonomi dan kebijakan publik, bukanlah sekadar cerita tentang seorang pahlawan.
Ini adalah sebuah studi kasus yang mencerminkan realita kesejahteraan para abdi negara di Indonesia.
Untuk memahami konteksnya, mari kita bedah struktur pendapatan seorang polisi dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka).
Gaji mereka tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gaji Anggota Polri, seorang Bripka (Golongan II) dengan masa kerja 17 tahun memiliki gaji pokok pada kisaran tertentu.
Baca Juga: Viral Aksi Emak-emak Pati Buatkan Bekal untuk Massa Demo Tuntut Pemakzulan Bupati Pati
Tukin Ini adalah komponen terbesar dari take-home pay seorang polisi, yang besarannya ditentukan oleh kelas jabatan.
Termasuk tunjangan keluarga (istri/anak), tunjangan pangan (beras), dan tunjangan lainnya.
Jika ditotal, pendapatan bulanan seorang Bripka kemungkinan besar berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Bangka Belitung (sekitar Rp3,6 jutaan pada tahun 2024).
Namun, di sinilah letak perdebatannya: apakah upah minimum sama dengan upah layak?
Upah Minimum hanya dirancang untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang pekerja lajang.
Sementara Bripka Fardiansyah adalah kepala keluarga yang harus menanggung biaya hidup istri dan anak-anak, yang meliputi: