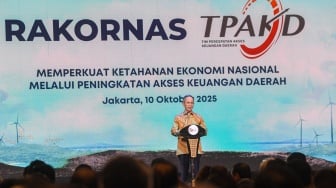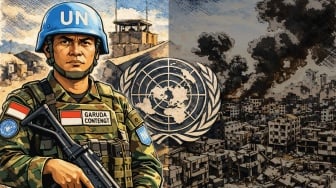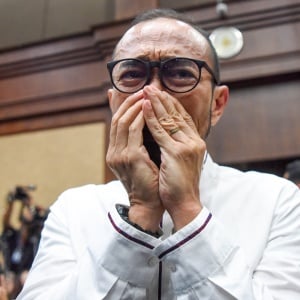Suara.com - Indonesia Sustainability Forum (ISF) yang ketiga baru saja berlangsung pada 10-11 Oktober 2025 di Jakarta. Pemerintah Indonesia menegaskan target menjadi pusat investasi hijau di Asia Tenggara dengan adanya forum tersebut. Tahun lalu ISF dalam klaimnya menghasilkan 12 kesepakatan termasuk di antaranya kesepakatan ekspor 3,4 gigawatt energi terbarukan ke Singapura senilai USD 25-30juta. Bisa dapat dipastikan kalau tahun ini pemerintah akan menargetkan lebih banyak komitmen investasi berkelanjutan dengan mengundang perwakilan dari dunia usaha, filantropi, dan family office untuk berinvestasi di Indonesia.
Konferensi megah seperti ISF dengan berbagai narasumber nasional dan global kerap membahas keberlanjutan dengan bahasa kebijakan tingkat tinggi, inovasi teknologi , dan investasi jutaan dolar. Di sana, kata-kata seperti “investasi hijau”, “pembiayaan campuran”, dan “kolaborasi lintas sektor” akan memenuhi panggung. Nyatanya jauh dari pembahasan panggung ISF, perwakilan masyarakat sipil di berbagai daerah secara hening mengerjakan imajinasi aksi iklim dengan menggabungkan inovasi teknologi dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Mengambil cerita dari tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bekasi, Yogyakarta, dan Kalimantan, kita dapat melihat bagaimana hujan, hutan, dan bahkan tinja dapat membantu mengatasi permasalahan iklim.
Inovasi Berkelanjutan dari Hujan, Hutan, dan Tinja
Di Gunung Kidul, Yogyakarta, kekeringan sudah lama dianggap takdir. Setiap musim kemarau, sumur mengering, tanaman mati, dan banyak petani memilih pergi ke kota menjadi buruh bangunan.
“Kalau tidak ada air, hidup berhenti,” ujar seorang warga mengingat masa itu.
Namun kelompok tani di Dusun Temon Kabupaten Gunung Kidu menolak menyerah. Bersama Yakkum Emergency Unit (YEU), sebuah organisasi kemanusiaan yang kini aktif dalam inisiasi adaptasi iklim, mereka membangun sistem sederhana untuk menampung hujan dan menyalurkannya kembali ke ladang melalui pipa-pipa bertekanan rendah yang diatur teknologi IoT. Mengandalkan gravitasi, panel surya, dan sensor murah yang mereka rakit sendiri, sistem ini berjalan tanpa pompa listrik.
Kini enam tandon besar berdiri di puncak bukit, menampung ribuan liter air setiap musim hujan. Dari situ, sprinkler kecil memercikkan embun buatan yang menghidupkan lahan di bawahnya. Ladang yang dulu gersang kini hijau sepanjang tahun. Panen meningkat, anak-anak muda kembali bertani. Bagi mereka, menampung hujan bukan hanya urusan teknologi, tapi juga soal martabat dan kemampuan untuk bertahan di tanah sendiri.
Dari tanah kering di selatan Jawa, kita bergeser ke jantung Kalimantan Barat, tempat hutan hujan yang dulu penuh suara burung pernah nyaris hilang.
Baca Juga: BCA Syariah Dorong Pemberdayaan UMKM Lewat Semangat Keberagaman di Bali Mester
Sekitar tahun 2000, masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung banyak yang menebang pohon, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk membiayai kesehatan. Harga berobat tinggi karena jauhnya jarak ke layanan kesehatan yang memadai. Pada 2007, Alam Sehat Lestari (ASRI) membawa ide yang tampak sederhana tapi revolusioner: siapa pun bisa berobat, dan pembayaran bisa dilakukan tidak harus dengan uang, tapi juga dengan bibit pohon. Masyarakat diberikan diskon biaya berobat yang semakin besar jika masyarakat terus menjaga hutan.
Lebih dari 1 dekade setelah program dijalankan, jumlah masyarakat yang terlibat penebangan ilegal turun signifikan. Ratusan hektar hutan kembali hijau, dan puluhan spesies yang terusir karena hilangnya hutan kini kembali ke rumahnya. ASRI menyebutnya aksi planetary health: ketika manusia dan hutan dapat pulih bersama.
“Dulu kami menebang untuk hidup,” kata seorang warga, “sekarang kami menanam untuk masa depan anak kami.”
Jika ASRI memulihkan hubungan antara manusia dan hutan, Gringgo Indonesia menantang sesuatu yang bahkan lebih tabu: tinja. Di Bekasi, mereka melihat tumpukan limbah domestik yang selama ini dianggap masalah, dan bertanya: mengapa tidak dijadikan sumber energi? Dari pertanyaan itu lahir Biocore, inovasi yang mengubah lumpur tinja menjadi briket bahan bakar bersih.
Pabrik mini mereka ditempatkan dekat instalasi pengolahan limbah agar biaya logistik rendah dan produksi bisa dikontrol secara digital. Dengan sensor IoT, mereka memantau suhu dan tekanan pembakaran, menghasilkan briket dengan emisi karbon lebih rendah daripada batu bara maupun kayu.
“Masalahnya bukan di teknologi,” ujar Febriadi Pratama salah satu pendiri Gringgo Indonesia, “tapi di cara kita memandang kotoran. Kalau cara pandang bisa diubah, nilainya ikut berubah.” Dari sesuatu yang menjijikkan lahir bahan bakar bersih; dari yang dibuang, tercipta kehidupan baru.
Imajinasi dan Investasi Hijau
Pendekatan seperti yang dilakukan YEU, ASRI, dan Gringgo – yang berangkat dari keberanian membayangkan ulang relasi manusia dan alam – sering kali tidak mendapat tempat dalam sistem pembiayaan iklim yang kaku. Investasi hijau besar masih lebih suka membangun pembangkit atau kawasan industri, bukan menanam gagasan di tingkat akar rumput. Padahal justru di sanalah daya tahan dan inovasi tumbuh di antara masyarakat yang bertemu langsung dengan krisis air, udara, dan tanah.
ISF akhir pekan ini menegaskan upaya pemerintah untuk merealisasikan potensi investasi hijau sebesar USD 200 miliar hingga 2030. Selain itu filantropi dan family office yang mulai kerap dilibatkan oleh pemerintah dalam skema pembiayaan hijau, memiliki ruang penting daripada sekedar ikut menambahkan besaran nominal pada komitmen tingkat tinggi di konferensi tersebut. Dengan karakter pembiayaan filantropi yang fleksibel, semestinya filantropis dapat memperkuat imajinasi perubahan seperti apa yang layak didanai. Filantropi dapat menyalakan percikan di tempat yang belum dijangkau pasar, membiayai risiko yang terlalu kecil untuk investasi hijau, tetapi terlalu besar untuk diabaikan.
Hujan, hutan, dan tinja – tiga hal yang kerap kita anggap sepele – telah menunjukkan bahwa imajinasi yang didukung dapat membawa perubahan pada masyarakat. Dan mungkin, banyak imajinasi sejenis dan lebih besar lahir di luar sana jauh dari panggung konferensi dan target pembiayaan investasi hijau.***