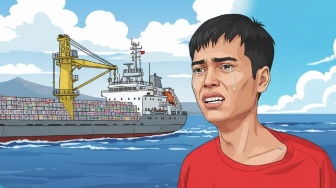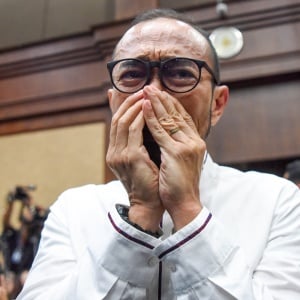Penggunaan asas oportunitas dijamin dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan juga mengamanatkan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani.
Tidak hanya dalam kewenangan seponering, dalam menjamin pelaksanaan asas oportunitas bisa juga di exercise dengan kewenangan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Pelaksanaan asas oportunitas semestinya tidak semata-mata hanya diberikan untuk pejabat dengan kasus-kasus berlatar belakang politis, tetapi seharusnya malah lebih tepat diprioritaskan untuk kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, utamanya dalam konteks pandemi Covid-19.
Memaksimalkan peran jaksa menggunakan asas oportunitas juga sejalan dengan arah pembaruan hukum di Indonesia yang mempromosikan restorative justice untuk diterapkan dari awal sistem peradilan pidana khususnya ketika proses sebelum persidangan. Arah pemidanaan yang bukan lagi bertumpu pada pembalasan/retributif harus dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum yang bekerja dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana, tidak terkecuali jaksa.
Sehingga dalam kasus-kasus seperti itu sebelum melimpahkan ke pengadilan, jaksa perlu mempertimbangkan peluang penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Melihat dengan kacamata lebih luas bahwa tujuan intervensi tersebut adalah untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dan memastikan bagaimana pelaku dapat kembali hidup di tengah masyarakat. Bentuk intervensi tersebut tidak selalu harus melalui penghukuman terhadap pelaku.