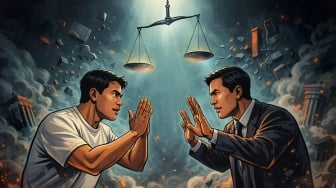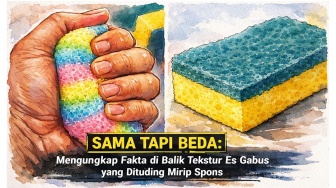Suara.com - Di atas kertas, Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk memimpin transisi energi, potensi tenaga surya lebih dari 200 gigawatt, berbagai dokumen perencanaan yang ambisius, dan komitmen mencapai net zero emission pada 2060.
Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Realisasi pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) justru tertinggal jauh.
Sejumlah pakar menilai, penghambat utamanya bukan pada kekurangan sumber daya atau visi, melainkan pada hal yang lebih mendasar: mekanisme pengadaan yang tak efisien, tidak transparan, dan minim insentif bagi investor.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 memang terlihat progresif. Tapi sejarah versi sebelumnya menunjukkan bahwa antara angka dan realisasi terbentang jurang yang belum tertutup.

“Tanpa pembenahan serius terhadap mekanisme pengadaan, ambisi transisi energi akan menjadi sekadar lembaran dokumen,” tegas Senior Strategist di Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini seperti dikutip dari ANTARA.
Ia menilai, meskipun Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 sudah memberikan fleksibilitas skema jual beli listrik antara pengembang dan PLN, itu belum cukup.
“Ekosistem pengadaan harus menjunjung prinsip keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan,” lanjutnya.
Masalah klasik seperti pengadaan lahan juga masih menjadi batu sandungan.
“Pemerintah perlu memberikan jaminan, terutama dalam aspek pengadaan lahan… tanpa mekanisme pembagian risiko yang adil dan jaminan memadai, investasi akan terus menjauh,” tambahnya.
Baca Juga: Dukung Transisi Energi Bersih, ZONAEBT Resmi Rilis Sertifikat REC ke Publik
Hal serupa disampaikan oleh Dody Setiawan, Analis Senior Iklim dan Energi dari EMBER. Menurutnya, untuk mencapai target tambahan PLTS dan PLTB sebesar 868 MW per tahun, empat kali lipat dari capaian sebelumnya, dibutuhkan bukan hanya target tanggal operasional, tapi peta jalan proyek yang nyata dan terstruktur.
“Mereka memerlukan peta jalan yang realistis, termasuk pipeline proyek dengan jadwal tender dan konstruksi yang jelas,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa ketidakpastian birokrasi dan proses yang lamban membuat banyak investor menunda keterlibatan mereka. “Perlu ada debottlenecking proses, supaya tidak hanya investor besar yang mampu bertahan, tapi juga pelaku usaha dalam negeri punya ruang bertumbuh,” katanya.
Persoalan ini juga menjadi fokus kajian akademik. Artikel ilmiah “The country of perpetual potential” karya Alin Halimatussadiah (FEB UI) dan tim peneliti lintas kampus menyebut pengadaan sebagai hambatan utama investasi EBT.
Studi itu menyoroti potensi konflik kepentingan karena PLN berperan ganda sebagai pembeli dan produsen, dan menyarankan perlunya reformasi institusional agar mekanisme pengadaan lebih independen dan terbuka.
Kritik juga datang dari Team Leader Iklim dan Energi Greenpeace Indonesi, Bondan Andriyanu. Ia mencermati bahwa dalam RUPTL terbaru, sebagian besar rencana pembangunan pembangkit EBT justru dijadwalkan setelah 2030.
“68 persen dari total rencana pembangkit EBT justru ditempatkan pada tahun 2030 dan setelahnya… Pola ini persis dengan RUPTL 2021–2030,” kata Bondan. Menurutnya, ini menunjukkan kecenderungan untuk menunda alih-alih mempercepat.
Dampaknya? “Strategi seperti ini memperlemah kredibilitas pemerintah dan menempatkan Indonesia dalam risiko ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.”
Vietnam menjadi contoh kontras. Dalam dua tahun saja, negara itu menambah lebih dari 11 GW kapasitas tenaga surya lewat skema sederhana feed-in tariff. Sementara Indonesia, yang potensinya jauh lebih besar, baru menyentuh angka realisasi di bawah 1,5 GW.
Transisi energi bukan sekadar proyek teknis, tetapi persoalan kebijakan struktural dan keberanian politik. Pemerintah baru dengan mandat kuat kini punya peluang mengubah arah, jika benar-benar menyiapkan otoritas pengadaan independen, menyusun timeline kredibel, memperbarui RUPTL secara dinamis, dan melibatkan pelaku usaha serta masyarakat lebih luas.
Karena pada akhirnya, seperti yang digarisbawahi dalam laporan tersebut, energi terbarukan bukan hanya soal panel surya dan turbin angin. Ini soal kedaulatan masa depan, keadilan sosial, dan hidup generasi berikutnya.