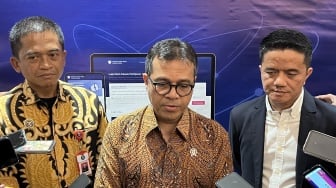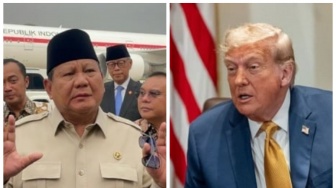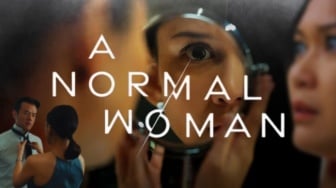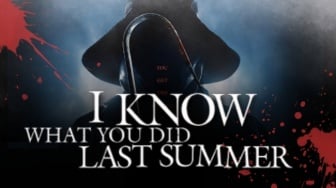Suara.com - Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menyebut pengalihan data pribadi WNI ke Amerika Serikat tidak melanggar prinsip HAM sontak menjadi pusat kontroversi.
Di atas kertas, jaminannya terdengar logis: selama prosesnya tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), segalanya akan aman dan terkendali.
Ia menekankan bahwa pertukaran data tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan dengan tata kelola yang aman dan terukur.
"Selama dijalankan berdasarkan aturan yang ada, maka tidak ada pelanggaran terhadap prinsip HAM," ujar Pigai dikutip Selasa (29/7/2025).
Pernyataannya menggarisbawahi bahwa kerangka hukum Indonesia telah disiapkan untuk mengawasi transfer data lintas negara secara bertanggung jawab.
Secara teori, UU PDP memang menjadi benteng yang dirancang untuk melindungi setiap informasi pribadi warga dari penyalahgunaan.
Namun, di ruang publik yang riuh, jaminan tersebut disambut dengan skeptisisme mendalam, bukan tanpa alasan.
Kredibilitas pernyataan Pigai dipertaruhkan di hadapan memori kolektif masyarakat mengenai penegakan HAM di Indonesia.
Bagi banyak warga, terutama aktivis dan korban, masa jabatan seorang pejabat HAM diukur dari kemampuannya menuntaskan kasus-kasus yang menggantung.
Baca Juga: Amerika Sumringah Dapat Data RI, Pemerintah: Bukan Info Pribadi dan Strategis
Kenyataannya, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tak kunjung menemukan titik terang dan keadilan, meninggalkan luka lama yang terus menganga.
Kegagalan inilah yang membangun tembok ketidakpercayaan yang kini harus dihadapi oleh Pigai.
Ketika sosok yang rekam jejaknya dalam penegakan HAM dianggap belum memuaskan oleh sebagian besar publik mengeluarkan jaminan, keraguan pun muncul secara alami.
Pertanyaannya menjadi lebih fundamental: bagaimana publik bisa memercayai jaminan perlindungan HAM dalam ranah digital dari figur yang dinilai belum berhasil menuntaskan pelanggaran HAM di dunia nyata?
Pernyataan langsung Pigai alih-alih menenangkan, justru memicu perdebatan lebih lanjut.
Argumennya yang berlandaskan kepatuhan hukum pada UU PDP seolah mengabaikan konteks yang lebih besar: ekosistem digital Indonesia yang keropos dan rentan.
Rentetan kasus kebocoran data—mulai dari data kependudukan, pemilih, hingga asuransi kesehatan—menjadi bukti nyata bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang tanpa kompromi dan infrastruktur keamanan yang kokoh.
Di tengah realitas ini, data pribadi WNI telah lama menjadi komoditas ilegal yang diperjualbelikan oknum kepada pihak asing.
Ironisnya, saat negara gagal melindungi data dari pasar gelap, kini muncul wacana untuk mentransfernya secara resmi dengan imbalan keuntungan ekonomi.
Kebijakan penurunan tarif 19 persen dari AS, yang berpotensi menjadi "pemanis" kesepakatan di era pemerintahan Prabowo, menempatkan warga dalam posisi dilematis.
Apakah keuntungan ekonomi ini sepadan dengan menyerahkan kunci data pribadi kepada negara lain, dengan jaminan dari figur yang kredibilitasnya tengah dipertanyakan oleh rakyatnya sendiri?