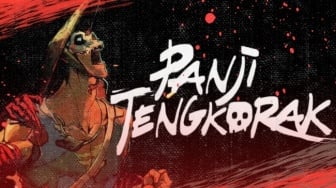Suara.com - Rancangan revisi Undang-Undang Kehutanan (UUK) tengah dibahas DPR RI. Ini adalah momen penting untuk mengakhiri warisan tata kelola hutan yang masih berwatak kolonial.
UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dianggap tak lagi mampu menjawab tantangan masa kini. Konflik lahan, deforestasi, hingga marjinalisasi masyarakat adat masih terus terjadi.
Pakar kehutanan menyebut, UUK bias daratan dan mengabaikan perspektif kepulauan. Bagi wilayah seperti Maluku dan Papua, ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi soal hilangnya ruang hidup dan sumber pangan.
Peneliti dari ICEL, Difa Shafira, menyatakan pokok materi revisi UUK yang dibahas Panja RUUK Komisi IV dan Badan Keahlian DPR RI tidak menyentuh akar persoalan.
“Pokok materi tersebut tidak menjawab masalah substansial dan masih mempertahankan pendekatan negara-sentris,” ujarnya. Difa menegaskan bahwa deforestasi seharusnya bisa dicegah dengan memperkuat sistem pemantauan dan penegakan hukum. UUK harus jadi perlindungan utama atas kekayaan sumber daya alam Indonesia.
“Fungsi hutan seharusnya hanya mengatur fungsi hutan pokok dan fungsi hutan cadangan untuk dipulihkan. Ini penting karena Indonesia punya komitmen di tingkat global untuk menekan laju deforestasi, yakni National Determined Contribution,” tegasnya.
Perubahan paradigma menjadi kunci.

“Dekolonisasi hutan mensyaratkan perubahan cara pandang—dari negara sebagai pengelola utama menjadi rakyat sebagai pilar utama,” kata Dr. Yance Arizona dari Fakultas Hukum UGM.
Ia mengkritik bahwa UUK masih bertentangan dengan semangat keadilan dalam UU Pokok Agraria (UUPA) yang membongkar doktrin kolonial domein verklaring.
Baca Juga: Konsesi dalam Bayang Konglomerat: Bisnis Karbon atau Kapitalisme Hijau?
Sajogyo Institute Kiagus M. Iqbal menambahkan, UUPA tidak melihat alam sebagai sekadar sumber daya teknokratis, melainkan sebagai Sumber-Sumber Agraria (SSA) yang merepresentasikan relasi sosial, ekologis, dan kultural.
“Asas ini adalah cara kolonial merampas tanah rakyat. Bagaimana mungkin tetap digunakan di era kemerdekaan?” tanyanya soal masih digunakannya asas domein verklaring dalam UUK.
Sorotan juga datang dari Erwin Dwi Kristianto dari HuMa yang mengkritik konsep Hak Menguasai Negara dalam UUK. Baginya, ini bukan bentuk perlindungan, melainkan legitimasi atas perampasan ruang hidup masyarakat.
“Padahal, banyak wilayah yang tidak pernah dikuasai raja maupun negara,” tegasnya.
Revisi UUK harus berpihak pada keadilan ekologis.
“Hutan harus dipandang sebagai bagian penting dari sistem penyangga kehidupan, bukan sekadar objek produksi,” ujar Mohamad Burhanudin dari Yayasan Kehati.
Menurutnya, pendekatan hukum yang baru perlu mengakui peran masyarakat adat sebagai penjaga utama ekosistem. Ia juga menyoroti masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidup mereka.
Burhanudin menegaskan, sektor kehutanan saat ini bermasalah dalam transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
“Kasus-kasus tumpang tindih izin, penerbitan izin di kawasan rawan bencana, hingga lemahnya pengawasan atas korporasi besar menunjukkan bahwa tata kelola sektor kehutanan belum berpihak pada keberlanjutan dan keadilan.”
Masalah teknokratisasi hutan juga dikritik. Dr. Martua T. Sirait dari Samdhana Institute menekankan pentingnya pendekatan etnografis dalam penetapan kawasan hutan. Menurutnya, proses saat ini bersifat sepihak dan hanya bersandar pada pendekatan administratif.
“Kawasan hutan sering kali tidak mendapat legitimasi sosial dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Kondisi ini dialami langsung oleh masyarakat di Maluku.
“Masyarakat kaget ketika tapal batas kawasan hutan dipasang pada 2020–2022 di rumah-rumah, kebun-kebun, dan hutan-hutan,” kata O.Z.S. Tihurua dari KORA Maluku. Sosialisasi minim, dan masyarakat baru sadar bahwa tanah yang telah mereka kelola sejak lama masuk ke dalam kawasan hutan negara.
UUK dinilai tidak mempertimbangkan karakter geografis kepulauan.
“Mengelola pulau kecil harus penuh dengan kehati-hatian dan tidak bisa disamakan dengan pulau besar,” jelas Prof. Agustinus Kastanya dari Universitas Pattimura.
Juru Kampanye Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga, menyimpulkan bahwa UUK perlu diganti total.
“UUK yang baru merupakan jawaban komprehensif atas persoalan tata kelola hutan saat ini,” tegasnya. DPR RI dan pemerintah harus terbuka pada kritik. Apalagi, kontribusi sub sektor kehutanan terhadap ekonomi sangat kecil dibanding dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.