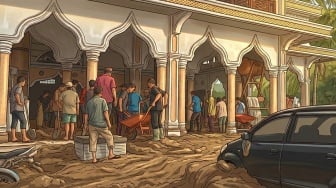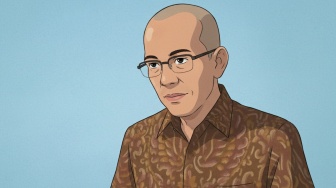-
- Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan perdebatan moral.
- Bangsa ini tampak ingin berdamai dengan masa lalu tanpa keberanian menghadapi kebenaran.
- Penghargaan terhadap penguasa otoriter mengancam standar moral bangsa dan menghapus makna keadilan sejarah.
Suara.com - Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menimbulkan guncangan moral yang sulit diabaikan.
Ia bukan sekadar penghargaan terhadap sosok yang pernah memimpin bangsa selama tiga dasawarsa, melainkan sebuah deklarasi politik tentang bagaimana negara ingin mengingat dirinya sendiri.
Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai pengakuan atas jasa besar dalam pembangunan dan stabilitas nasional.
Namun di sisi lain, ia menimbulkan perasaan getir di hati mereka yang pernah hidup di bawah bayang represi, karena penghormatan itu terasa seperti penegasan bahwa luka mereka tidak pernah penting.
Bagi banyak orang, Soeharto memang hadir sebagai simbol keberhasilan pembangunan. Jalan raya, irigasi, pabrik, dan program swasembada pangan menjadi kenangan masa keemasan yang mudah dirayakan.
Tetapi sejarah tidak hanya dihitung dari beton dan angka pertumbuhan. Di balik 'stabilitas' itu berdiri sistem yang menutup mulut, membungkam kritik, dan menanam ketakutan sebagai mekanisme kekuasaan.
Orang-orang ditahan tanpa pengadilan, aktivis diculik, wartawan disensor, dan korupsi dijadikan bagian dari tata kelola negara.
Ketika figur yang berada di puncak sistem itu kini dinobatkan sebagai pahlawan, banyak korban merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekecewaan—sebuah kehilangan makna tentang apa itu keadilan.
Bangsa ini tampaknya ingin cepat berdamai dengan masa lalunya, tanpa pernah benar-benar menghadapinya. Kita ingin melupakan karena mengingat terlalu menyakitkan.
Baca Juga: Marsinah: Buruh, Perlawanan, dan Jejak Keadilan yang Tertunda
Namun yang sering luput disadari, luka yang tidak diakui tidak akan pernah sembuh. Penetapan ini, dalam pandangan banyak korban, bukanlah penutup sejarah, melainkan pembuka luka baru.
Ia seperti penghapus yang menghilangkan bekas darah dari catatan nasional, tanpa pernah menjelaskan mengapa darah itu tumpah.
Ketika Sejarah Ingin Dilupakan
Negara seolah lupa bahwa penghargaan adalah bentuk penilaian moral.
Ketika penghargaan tertinggi diberikan kepada tokoh yang di bawah kepemimpinannya lahir begitu banyak penderitaan, maka bangsa ini sesungguhnya sedang menegosiasikan nilai kemanusiaannya sendiri.
![Massa dari Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Senin (10/11/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/10/58392-aksi-tolak-soeharto-jadi-pahlawan-di-kementerian-kebudayaan.jpg)
Apakah pembangunan ekonomi dapat menebus hilangnya kebebasan? Apakah ketertiban sosial bisa dijadikan alasan untuk meniadakan hak asasi manusia?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak pernah dijawab secara jujur oleh negara, hanya diredam oleh nostalgia tentang harga beras dan minyak tanah yang murah.
Di titik ini, gugatan terhadap keputusan tersebut menjadi wajar, bahkan perlu. Bukan hanya karena sebagian besar rakyat merasa tidak dilibatkan dalam penilaian sejarah yang begitu besar, melainkan karena keputusan ini mengandung konsekuensi moral bagi arah bangsa ke depan.
Mungkinkah keputusan itu dibatalkan? Secara administratif mungkin tampak sulit, tetapi secara moral sangat mungkin—sepanjang bangsa ini masih memiliki nurani dan keberanian untuk meninjau ulang langkahnya.
Tidak ada keputusan politik yang lebih tinggi dari kebenaran sejarah. Negara yang sehat justru mampu mengoreksi dirinya sendiri.
Kita tidak sedang membicarakan dendam masa lalu. Kita sedang berbicara tentang keadilan yang tertunda. Tentang mereka yang tak pernah mendapat kesempatan untuk bersuara.
Tentang ibu-ibu yang kehilangan anaknya tanpa tahu di mana jasad mereka dikuburkan. Tentang mahasiswa yang hilang di malam hari dan tak pernah kembali.
Tentang wartawan yang dibungkam, cendekiawan yang dikucilkan, dan generasi yang tumbuh dalam ketakutan untuk berpikir berbeda.
Mereka semua adalah bagian dari cerita yang kini terancam dihapus oleh keputusan negara yang terlalu tergesa melupakan.
Ironisnya, bangsa ini bukan tidak tahu bagaimana seharusnya berdamai dengan sejarah. Kita telah melihat contoh dari banyak negara yang memilih jalur kebenaran.
Jerman tidak pernah menghapus tragedi Nazi dari buku pelajarannya. Afrika Selatan menegakkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk membuka luka bersama, bukan menutupnya.
Argentina menghukum pelaku pelanggaran HAM, bahkan puluhan tahun setelah kediktatoran berakhir. Sementara Indonesia memilih cara paling nyaman: diam.
Kita membiarkan sejarah diselimuti kabut nostalgia, membiarkan generasi muda mengenal Soeharto hanya sebagai wajah tersenyum di poster-poster 'pahlawan pembangunan.'
Mereka yang menolak lupa tidak sedang menolak bangsa, melainkan sedang menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan jiwanya.
Kegagalan terbesar kita bukan pada masa lalu yang kelam, melainkan pada ketakutan untuk menatapnya dengan jujur.
Setiap bangsa memiliki masa kelam, tetapi hanya bangsa yang berani mengakuinya yang akan tumbuh menjadi dewasa.
Indonesia justru memilih cara sebaliknya—memutihkan catatan sejarah dan menganggap luka sebagai aib yang harus dilupakan. Padahal, pengakuan terhadap luka bukan tanda kelemahan, melainkan syarat bagi penyembuhan.
Kebenaran yang Tak Bisa Dikubur
Penetapan ini mengirimkan pesan berbahaya: bahwa kekuasaan yang panjang dan hasil pembangunan dapat menebus pelanggaran terhadap kemanusiaan. Jika pesan itu diterima tanpa kritik, bangsa ini akan kehilangan standar moralnya.
Apa yang akan mencegah seorang penguasa di masa depan melakukan hal serupa, bila sejarah membuktikan bahwa seorang penguasa otoriter yang berkuasa lama dan akhirnya digulingkan rakyatnya sendiri, pada akhirnya mendapat gelar pahlawan?
Sebuah bangsa seharusnya menilai masa lalunya bukan dengan perasaan sentimental, melainkan dengan nurani yang jernih.
Mengakui keberhasilan Soeharto dalam pembangunan tidak harus diikuti dengan pengabaian terhadap pelanggaran yang terjadi di bawah pemerintahannya.
Dua hal itu bisa berdiri berdampingan bila negara berani jujur. Tetapi dengan menjadikan sosoknya pahlawan nasional, negara justru menutup kemungkinan dialog jujur itu.
Gelar kehormatan ini menjadi pagar simbolik yang menghalangi evaluasi moral yang seharusnya terus berlangsung.
Bagi korban, penetapan ini bukan akhir, melainkan awal perlawanan baru—perlawanan untuk mempertahankan kebenaran sejarah agar tidak digilas kenyamanan politik.
Mereka yang menolak lupa tidak sedang menolak bangsa, melainkan sedang menjaga agar bangsa ini tidak kehilangan jiwanya.
Penolakan terhadap pelupaan adalah bentuk cinta paling dalam kepada tanah air: cinta yang tidak mau bersekongkol dengan kebohongan.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat melupakan, melainkan yang paling berani mengingat. Karena mengingat berarti menghormati mereka yang pernah menderita agar penderitaan itu tak terulang.
Jika hari ini negara memilih memberi medali kepada penguasa masa lalu, biarlah rakyat yang menjaga agar medali itu tidak menghapus jejak air mata.
Sebab selama luka itu belum dipulihkan dengan kebenaran, setiap penghargaan yang lahir di atas penderitaan akan tetap terdengar seperti gema dari ruang gelap sejarah yang belum selesai—dan di sanalah suara para korban masih terus berbisik, menuntut kejujuran bangsa kepada dirinya sendiri.
Pius Lustrilanang
Eksponen Aktivis 98, Korban Penculikan Orde Baru