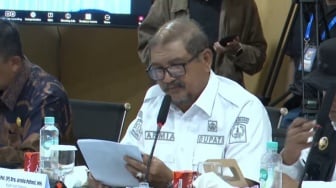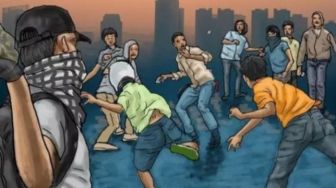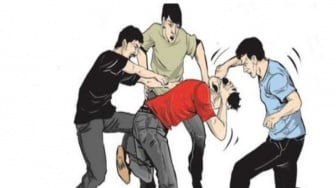Kelas menengah reformis lebih berkepentingan mendorong perubahan-perubahan institusional dan melakukan perlawanan-perlawanan yang sporadis. Tidak seperti yang dibayangkan kalangan liberal pluralis, dominannya bentuk aktivisme borjuis itu membuat elemen-elemen gerakan sosial di Indonesia kurang bisa menghadirkan tantangan dan ancaman yang berarti kepada kepentingan-kepentingan yang berupaya membalik agenda demokratisasi. Tanpa kekuatan politik progresif yang koheren, tidak akan ada perlindungan hak sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh kepada warga, yang adalah aspek-aspek esensial demokrasi.
Demokrasi Pasca 1998
Bagaimana dengan kehadiran demokrasi pasca 1998? Apakah ia semata hasil desakan dari bawah, terutama yang berasal dari elemen gerakan mahasiswa? Beberapa studi – terutama dari perspektif liberal pluralis – dan tentu saja para eksponen aktivis 1998 cenderung mengglorifikasi peran gerakan mahasiswa dalam menjatuhkan rezim otoriter Soeharto yang membuka jalan bagi lahirnya demokrasi.
Padahal, terdapat sejumlah kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya pergantian rezim. Pertama, krisis moneter telah membuka jalan adanya tekanan dari International Monetary Fund (IMF) – representasi kapitalisme neoliberal – yang tidak lagi menghendaki kekuasaan politik yang sentralistik dan terlampau interventif dalam mengatur ekonomi. Kedua, menguatnya friksi elemen pendukung rezim, terutama dari kalangan militer.
Dua faktor itu menegaskan bahwa kepentingan kapital turut berkontribusi menghadirkan institusi demokrasi di Indonesia. Di samping itu, tanpa difasilitasi faksi militer yang berseberangan dengan penguasa, hampir mustahil elemen gerakan mahasiswa 1998 dapat menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR).
Sebelumnya, aliansi serupa antara mahasiswa dan militer di tahun 1966 juga telah mengantarkan terjadinya pergantian rezim. Akan tetapi, alih-alih dapat mengawal perubahan, mahasiswa angkatan 1966 justru telah membuka jalan bagi konsolidasi militer di bawah kekuasaan Soeharto yang otoriter.
Fakta sejarah ini meruntuhkan pandangan yang melebih-lebihkan peran mahasiswa dan pemuda secara umum sebagai agen perubahan. Pada kenyataannya, kehadiran institusi demokrasi di Indonesia sangat terbatas, yakni sejauh ia tidak menghambat kepentingan kapital. Ini menunjukkan lemahnya gerakan mahasiswa dan elemen gerakan sosial lainnya dalam mendorong demokrasi untuk lebih jauh mewujudkan perlindungan hak sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh kepada warga.
Lebih jauh, gerakan mahasiswa sebagai aktor dominan dalam sejarah perubahan sosial di Indonesia pasca 1965 juga mesti dipahami dalam kaitannya dengan absennya politik kelas yang lebih berorientasi mendorong perubahan struktural.
Aktivisme Borjuis
Baca Juga: Hidup Orang Rimba Kala Covid-19: Terhindar dari Wabah Tapi Kelaparan dalam Hutan
Dominannya bentuk aktivisme borjuis bukan kasus unik di Indonesia. Tulisan-tulisan Kevin Hewison dan Garry Rodan, ilmuwan sosial yang menekuni studi tentang gerakan sosial di Asia, telah menunjukkan bahwa kecenderungan yang sama dapat ditemui di beberapa tempat seperti di negara-negara Asia Tenggara yang lahir dari kondisi struktural serupa: (1) corak kapitalisme yang menempatkan penguasaan atas akses dan kontrol institusi publik sebagai elemen pokok; serta (2) relatif absennya politik kelas warisan Perang Dingin.
Tidak adanya pengorganisasian berbasis kelas dalam arena politik ini yang kemudian melahirkan model aktivisme borjuis, terutama dalam bentuk organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dikenal sebagai non-government organization (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau civil society organization (CSO). Konsep “masyarakat sipil” menggantikan organisasi kelas yang sekaligus melunakkan tuntutan revolusi menjadi reformasi.
Kelas menengah reformis lebih berkepentingan mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, pluralisme, anti-korupsi, keadilan lingkungan, serta isu-isu sektoral lainnya dengan mendorong reformasi institusi serta membuat suatu desain kebijakan yang dianggap dapat menopang penguatan demokrasi ketimbang berkeinginan mengubah secara radikal tatanan ekonomi politik dan struktur kekuasaan. Mereka juga cenderung tidak memiliki strategi jangka panjang dalam memajukan agenda demokratisasi.
Strategi Politik yang Sporadis
Nihilnya strategi jangka panjang membuat kelas menengah reformis sangat terfragmentasi sebagai kekuatan politik. Strategi politik yang dijalankan juga cenderung elitis, sporadis, dan reaksioner.
Kelas menengah reformis menggunakan lobi-lobi – terutama saat telah bekerja di lembaga donor – atau memasuki gelanggang politik formal untuk mempengaruhi kebijakan publik meski tanpa ditopang kekuatan politik progresif yang kuat. Karena tidak memiliki kendaraan politik formal, saat pemilihan umum, elemen aktivisme borjuis kerap berharap perubahan dapat dilakukan oleh seorang politisi yang dianggap reformis. Akan tetapi, alih-alih dapat mendorong perubahan dan memajukan agenda demokratisasi, mereka yang memasuki gelanggang politik formal serta politisi reformis itu menduplikasi praktik-praktik predatorisme.