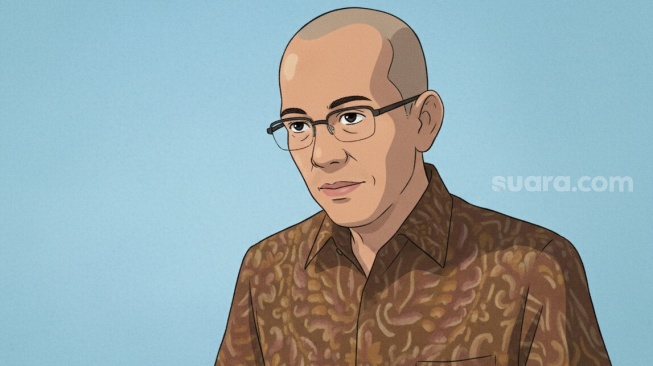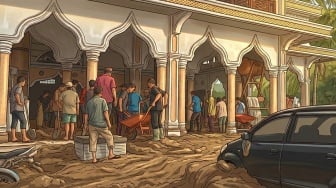- Marsinah, buruh perempuan berani, memperjuangkan hak-hak pekerja di tengah represi Orde Baru yang menindas.
- Pembunuhannya tahun 1993 tak terungkap, proses hukum cacat, dan keadilan terhenti tanpa pelaku dihukum.
- Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2025, namun negara belum menuntaskan kebenaran dan tanggung jawab moralnya.
Suara.com - Marsinah lahir di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, pada 10 April 1969. Ia tumbuh sebagai perempuan pekerja yang sederhana namun berani.
Di pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, Marsinah dikenal vokal membela kawan-kawannya—menuntut hak cuti haid, cuti melahirkan, upah layak, dan kebebasan berserikat. Bukan pemimpin serikat formal, tetapi bagi rekan-rekannya, Marsinah adalah suara keberanian di lantai produksi.
Awal 1993, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian upah minimum. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan buruh, namun di mata pengusaha menjadi beban baru.
Di CPS, ketegangan meningkat. Buruh menuntut penerapan upah minimum, perusahaan menolak atau menunda. Dalam situasi itu, Marsinah berdiri di garis depan, menjadi juru bicara spontan.
Di masa Orde Baru, keberanian semacam itu dianggap subversif. Campur tangan aparat militer dalam urusan perburuhan kala itu lazim, dan sering menjadi alat untuk menekan.
Pada 3–4 Mei 1993, buruh CPS menggelar mogok kerja. Marsinah kembali bersuara lantang. Setelah mogok, beberapa buruh dipanggil aparat militer. Situasi yang semula industrial berubah menjadi urusan 'keamanan'.
Malam 5 Mei, Marsinah hilang setelah berusaha mencari rekan-rekannya yang ditahan. Tiga hari kemudian, jasadnya ditemukan di Nganjuk, penuh luka penyiksaan. Laporan forensik menyebutkan kekerasan fisik dan seksual.
Dari situ, nama Marsinah tak lagi sekadar nama buruh pabrik—ia menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang membungkam.
Keadilan yang Macet dan Luka yang Tak Sembuh
Kematian Marsinah memantik solidaritas luas. Ia menerima Yap Thiam Hien Award (1993) sebagai bentuk penghormatan atas keberaniannya. Tetapi ketika publik menuntut keadilan, negara justru tersesat dalam labirin hukum.
Polisi menahan delapan orang dari jajaran manajemen CPS. Mereka diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman.
Namun sejak awal, pegiat HAM menilai proses itu cacat: pengakuan diperoleh di bawah tekanan, bukti lemah, dan banyak fakta disembunyikan. Amnesty International serta Komnas HAM menyebutnya sebagai rekayasa kasus.
Tahun 1995, Mahkamah Agung membatalkan seluruh vonis. Delapan terdakwa dibebaskan karena bukti tak sah dan proses penyidikan melanggar hukum.
Sejak itu, kasus Marsinah kembali gelap. Tidak ada tersangka baru, tidak ada proses baru, tidak ada satu pun pelaku yang dijatuhi hukuman berkekuatan tetap.
Dugaan keterlibatan unsur militer yang sempat disinggung dalam laporan HAM tak pernah diselidiki tuntas. Secara formal, kasus ini berhenti; secara moral, luka itu tetap terbuka.
Hingga kini, Komnas HAM, YLBHI, dan berbagai jaringan advokasi terus menegaskan bahwa pengusutan kasus Marsinah belum menyentuh pelaku utama.
![Adik aktivis buruh Marsinah, Wijiyati menangis di balik foto kakaknya usai mengikuti upacara pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah dan sembilan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/10/56642-penganugerahan-gelar-pahlawan-nasional-marsinah.jpg)
Impunitas tetap berdiri tegak, dan di situlah akar kekecewaan publik: bukan karena negara tidak tahu, tapi karena negara tidak mau tahu.
Paradoks Kepahlawanan dan Amnesia Negara
Tiga puluh dua tahun kemudian, pada 10 November 2025, pemerintah menobatkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, bersama dengan Soeharto dan Abdurrahman Wahid.
Bagi gerakan buruh, pengakuan ini menjadi kebanggaan: untuk pertama kalinya, seorang buruh perempuan diakui sebagai pahlawan bangsa. Namun bagi banyak orang, keputusan itu menimbulkan paradoks moral.
Negara memang memuliakan Marsinah, tetapi pada saat yang sama menyatakan bahwa gelar itu 'tidak terkait' dengan penyelidikan ulang atas pembunuhannya.
Ia dihormati sebagai simbol, tapi belum diperlakukan sebagai korban yang pantas mendapat keadilan.
Paradoks itu semakin menyentak karena nama Marsinah diumumkan dalam upacara yang sama dengan Soeharto—penguasa yang sistemnya menormalisasi represi terhadap kaum buruh.
Bagi publik yang peka sejarah, kombinasi dua nama ini terasa seperti ironi yang sulit dicerna.
Negara seolah merayakan penindasan dan perlawanan dalam satu panggung yang sama, tanpa pernah menjelaskan apa yang sesungguhnya ingin ditegaskan: penghormatan, atau pelupaan?
Sampai hari ini, tidak ada satu pun pelaku pembunuhan Marsinah yang dihukum tetap. Pengadilan pernah menjatuhkan vonis, lalu Mahkamah Agung membatalkannya.
Ia dihormati sebagai simbol, tapi belum diperlakukan sebagai korban yang pantas mendapat keadilan.
Setelah itu, sunyi. Tidak ada pelaku baru, tidak ada rekonstruksi kasus, tidak ada permintaan maaf resmi. Keadilan berhenti di tengah jalan.
Hanya namanya yang kini hidup di monumen dan upacara kenegaraan, sementara kebenarannya dibiarkan membeku.
Marsinah bukan sekadar nama dalam daftar pahlawan. Ia adalah cermin relasi kuasa antara negara, pasar, dan rakyat pekerja di masa ketika kebebasan berserikat adalah kemewahan.
Pengakuan atas jasanya memperluas definisi kepahlawanan—dari perlawanan bersenjata menjadi perjuangan menegakkan keadilan sosial.
Namun tanpa keberanian negara menegakkan hukum, penghormatan itu tak lebih dari plakat yang dipoles sejarah.
Penutup: Pahlawan yang Masih Menunggu Keadilan
Hari ini, Marsinah dikenang sebagai simbol keberanian perempuan pekerja. Tapi penghormatan sejati tidak berhenti di seremoni dan gelar.
Ia menuntut tanggung jawab moral dan politik dari negara: membuka kembali berkas lama, mengaudit proses yang cacat, dan menuntut pertanggungjawaban mereka yang pernah berkuasa atas nyawa rakyat kecil.
Bila proses hukum tidak lagi memungkinkan, maka pengakuan kebenaran dan rehabilitasi moral harus menjadi jalan yang ditempuh.
Marsinah mengajarkan bahwa pahlawan tidak selalu lahir di medan perang. Kadang mereka muncul di ruang produksi, di antara mesin-mesin, di bawah bayang-bayang ketakutan.
Ia berjuang bukan untuk kemuliaan pribadi, melainkan untuk martabat manusia. Dan justru karena itu, kematiannya adalah ujian bagi bangsa ini: apakah kita mampu menegakkan keadilan bahkan bagi mereka yang tidak punya kuasa untuk memperjuangkannya sendiri.
Kini, setelah lebih dari tiga dekade, negara mungkin telah menaruh bunga di pusaranya. Tetapi keadilan—yang semestinya menyertai setiap penghormatan—belum juga hadir.
Marsinah telah menjadi pahlawan di atas panggung negara, namun di mata sejarah, ia tetap gugatan hidup: simbol keberanian yang menunggu kebenaran ditegakkan.
Pius Lustrilanang
Eksponen Aktivis 98, Korban Penculikan Orde Baru