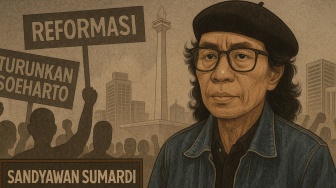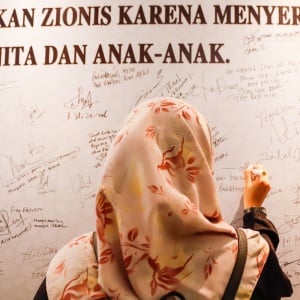Kalau itu sebenarnya dalam satu proses sosial yang bisa kita pahami, tapi tidak dengan serta-merta kita benarkan. Ini soal pembentukan suatu habitus baru oleh karena pandemi. Pada tahun awal, sekali pun dilarang, tetap saja ada yang sembunyi-sembunyi. Nah sekarang dilakukan, tapi dengan pengetatan yang lebih besar, tapi tetap terjadi ceceran-ceceran, orang berusaha untuk keluar. Kenapa masih ada begitu?
Habitus itu terbentuk dua tahun belakangan ini. Karena sudah dua tahun Covid-19-nya masih ada, plus dia juga tahu ada vaksin dan sebagainya, orang sudah mulai terbiasa hidup dalam situasi seperti itu, dan merasa lebih punya culture skill untuk "ngakalin" Covid.
Cuma kan, itu kan praktek kebudayaannya mencoba untuk mengakali pandemi. Yang kurang disadari adalah ketika dia mencoba mengakali berdasarkan pengalamannya selama dua tahun, si virus juga mengakali dengan cara lain yaitu mutasi dengan varian baru yang lebih ganas, lebih cepat menular.
Nah, ini yang jadi problem. Pemerintah khawatir akal-akalan virus lebih cepat dari akal-akalan kebudayaan orang. Itu yang sekarang terjadi, dan kita tentu boleh khawatir.
Untungnya, daerah-daerah merespon dengan baik. Kita lihat, sekali pun ada banyak pemudik yang akal-akalan dengan aneka macam cara untuk bisa pulang kampung, tapi dia juga berjumpa dengan mekanisme sosial yang baru di daerah.
Di daerah kita lihat ada istri yang melaporkan suaminya yang mudik ke RT, RW-RW membuka rumah karantina sendiri. Tahun lalu tidak ada lho ini. Ini artinya mekanisme sosial dari masyarakat kita juga tumbuh dalam merespon kecenderungan yang tidak bisa dihentikan ini.
Ini satu hal yang bagus. Sekali pun ada arus gerak yang sepertinya mau mengakali Covid, tapi di sisi lain ada pranata sosial baru yang dipraktikkan oleh masyarakat untuk menahan itu.
Dari situ, jelas mudik tidak bisa dihentikan. Ini fakta. Sekali pun demikian, pelarangan mudik masih harus terus dilakukan. Yang lebih jauh, kita mesti mencari cara bagaimana untuk mengantisipasi apabila terjadi penambahan kasus akibat dari arus yang merembes itu tadi.
Di media sosial ramai polemik "dilarang mudik tapi tempat wisata dibuka". Ini terkait kebijakan yang kontradiktif. Sebenarnya, situasi ini apakah akan berdampak pada efek psikologis dari masyarakat yang nekat mudik?
Baca Juga: Habib Nabil bin Ridho Al Habsyi: Bimbing Umat, Ulama Tak Bisa Jalan Sendiri
Iya, pasti dong. Jadi yang namanya pembatasan situasi pandemi, namanya juga social distancing, yang paling aman bagi kita dan orang lain itu adalah di rumah. Sederhananya, kita mencegah orang kumpul supaya kepadatan sosial itu merenggang serenggang-renggangnya.
Begini problemnya. Tadi kenapa saya sebut semantik problemnya, ketika dia pembukaan wisata dieksplisitkan dalam konteks lebaran dan liburan di Indonesia, maka itu akan dianggap sebagai anjuran. Itu dia problemnya. Semantik itu sangat penting dalam problem kebijakan.
Dengan (pembukaan wisata itu) diumumkan, seperti mengundang atau menyarankan. Nah, di situlah orang membaca ini sebagai inkonsistensi. Kalau mau sikap dasar dari larangan mudik kan untuk menjaga social distancing, tapi kenapa di sisi lain dibuka pariwisata. Itu artinya mendorong orang untuk kumpul di satu tempat.
Jadi faktor semantik itu penting, karena selalu membuat apa-apa yang sudah dipadatkan buyar. Lain kali menurut saya, kalau concern kita adalah medis, maka untuk hal yang tidak pokok atau bukan substansial seperti wisata, itu lebih baik tidak usah digunakan bahasa seperti itu. Justru harus dilakukan pengetatan di beberapa sektor di masa-masa mudik dan arus balik lebaran itu.
Jadi jangan kontradiktif. Orang dilarang mudik tapi wisata dibuka, itu kontradiktif. Akibatnya kegawatannya, concern dari krisisnya itu menjadi tidak terasa. Orang bertanya-tanya, ini lagi krisis atau tidak sih? Segawat itu atau tidak sih? Buktinya itu dibuka? Nah, itu dimensi kontradiktifnya, karena dia mengurangi dimensi kegawatan.
Ada hal kontradiktif lain, yaitu soal WNA China boleh masuk Indonesia sementara WNI dilarang mudik. Bagaimana ini pengaruhnya terhadap masyarakat?